Publikasi
Opini
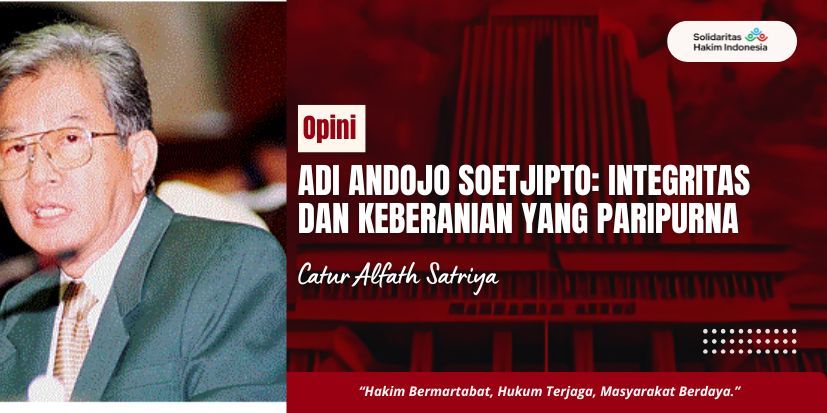
Adi Andojo Soetjipto: Integritas dan Keberanian yang Paripurna
Institusi pengadilan selalu berada dalam posisi yang problematis dalam sejarah bangsa Indonesia. Di masa kolonial, pengadilan dijadikan alat status quo oleh negara induk yang menghambat pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di zaman orde lama, pengadilan tidak lebih dari “perpanjangan tangan” revolusi ala Soekarno yang menafikan pemisahan dan perimbangan kekuasaan sehingga tidak ada lagi otonomi pengadilan. Di zaman orde baru, pengadilan diberikan independensi namun ternyata independensi yang semu, departemen dijadikan alat oleh eksekutif untuk “mencampuri” urusan yudisial yang berdampak pada putusan yang penuh dengan kontroversi pada saat itu. Permasalahan tersebut menjadi pemicu untuk memasukan agenda reformasi penegakan hukum dan peradilan ketika Indonesia memasuki periode baru reformasi pasca jatuhnya rezim Soeharto.
Pendahuluan
Dalam perjalanan sejarah, diskursus mengenai pengadilan baru mendapatkan proporsi yang tepat setelah Montesquieu menuliskan buku yang dalam bahasa inggris berjudul The Spirit of the laws. Di dalam buku itu Montesquieu mencetuskan doktrin apa yang kita kenal sekarang sebagai trias politica yang merupakan bentuk dari pembagian dan pemisahan kekuasaan. Doktrin trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu berbeda dengan doktrin pembagian dan pemisahan kekuasaan sebelumnya yang dilahirkan oleh John Locke. Montesquieu menjadikan kekuasaan yudisial menjadi kekuasaan tersendiri karena menurut Montesquieu kekuasaan yudisial harus independen dan tidak boleh diintervensi karena apabila diintervensi maka terbuka kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dasar pemikiran Montesquieu inilah yang digunakan sampai saat ini dalam membagi kekuasaan negara. Di setiap negara perlu adanya kekuasaan yudisial yang mandiri dan merdeka untuk menjadi negara yang demokratis. Arsitektur kekuasaan yudisial harus dibangun sedemikian rupa sehingga intervensi dari cabang kekuasaan yang lain tidak bisa dilakukan.
Namun, pada praktiknya menciptakan institusi pengadilan yang mandiri dan merdeka berdasarkan pemikiran Montesquieu bukanlah hal yang mudah. Institusi pengadilan mengalami pasang surut dalam posisi dan perannya di republik ini. Ketika masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, pengadilan di Indonesia hanya menjadi alat bagi pemerintah kolonial untuk menghukum usaha-usaha pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, posisi institusi pengadilan tidak menjadi lebih baik. Apalagi ketika Soekarno menjadi presiden, institusi pengadilan menjadi satu bagian dari kekuasaan eksekutif yang mengakibatkan pengadilan tidak bisa tumbuh menjadi institusi yang merdeka dan mandiri.
Angin segar terhadap institusi pengadilan yang merdeka sempat hadir pada zaman orde baru. Ketika itu pada tahun 1970, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 14 tahun 1970) lahir menggantikan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 19 tahun 1964 (selanjutnya disebut UU Nomor 19 tahun 1964). UU Nomor 19 tahun 1964 perlu direvisi karena secara normatif UU tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk bisa ikut campur dalam hal yang berkaitan dengan pengadilan. Namun, UU Nomor 14 tahun 1970 ternyata belum sepenuhnya mewujudkan institusi pengadilan yang mandiri dan merdeka. Di dalam Pasal 11 undang-undang tersebut, eksekutif masih bisa ikut “campur tangan” terhadap badan peradilan apabila berkaitan dengan organisasi, administratif, dan finansial. Selain itu, UU Nomor 14 tahun 1970 tidak sesuai dengan aspirasi hakim pada saat itu yang menuntut adanya kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang.
Di dalam perjalanannya, intervensi eksekutif terhadap pengadilan masih belum berhenti. Departemen Kehakiman dijadikan alat oleh eksekutif untuk melakukan intervensi terhadap suatu perkara. Bahkan intervensi tidak hanya dilakukan oleh Departemen Kehakiman namun juga oleh Mahkamah Agung yang mengintervensi pengadilan di bawahnya (intervensi internal). Intervensi ini dapat dilihat di dalam perkara Haris Murtopo yang melibatkan Jenderal Ali Murtopo dan perkara Jasin. Intervensi ini membuat semakin jelas bahwa rezim orde baru tidak memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi pengadilan.
Intervensi yang terjadi terhadap pengadilan pada khususnya dan kekuasaan kehakiman pada umumnya secara tidak langsung membuat institusi pengadilan semakin jauh dari cita-citanya. Semakin seringnya intervensi, maka sudah bisa dipastikan praktik korupsi akan sering terjadi. Di zaman orde baru intervensi kepada pengadilan dilakukan dengan kekuasaan atau uang. Intervensi kekuasaan terlihat pada waktu itu dalam perkara Kedung Ombo. Intervensi kekuasaan biasanya dilakukan oleh para politisi maupun pejabat yang kepentingannya terganggu terhadap perkara tersebut. Selanjutnya, intervensi uang yang biasanya dilakukan oleh pihak yang berperkara. Salah satu kasus yang menarik yang berhubungan dengan intervensi uang adalah kasus Gandhi Memorial School. Dari kasus Gandhi Memorial School inilah akhirnya inisiatif untuk melahirkan lembaga eksternal yang mengawasi hakim dan pengadilan muncul yaitu Komisi Yudisial. Kasus Gandhi Memorial School merupakan kasus yang memperlihatkan secara jelas bobroknya institusi pengadilan bahkan Mahkamah Agung pada waktu itu.
Di tengah turbulensi politik terkait dengan masa depan pengadilan di Indonesia muncul satu sosok hakim agung yang berintegritas dan pemberani dalam memerangi korupsi di tubuh Mahkamah Agung yaitu Adi Andojo Soetjipto.
Keberanian dan Integritas
Adi Andojo Soetjipto lahir pada tanggal 11 April 1932 di Yogyakarta. Sebagai anak yang lahir dari keluarga yang dekat dengan dunia pengadilan, Adi Andojo Soetjipto terinspirasi dengan ayahnya yang pada waktu itu menjadi hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung pada tahun 1956. Ketika itu, ayah Adi Andojo Soetjipto sedang memeriksa suatu perkara dan pengacara yang mendampingi terdakwa mendekati sang ayah kemudian menawarkan sebuah oplet yang akhirnya ditolak mentah-mentah oleh sang ayah. Apa yang dilakukan oleh sang ayah kemudian ditiru oleh Adi Andojo Soetjipto ketika menjadi hakim pertama di Pengadilan Negeri Madiun pada tahun 1960. Ketika itu Adi Andojo Soetjipto menolak pemberian jam tangan Omega dan kain wol yang diberikan oleh terdakwa dengan tujuan agar terdakwa dibebaskan. Penolakan tersebut akhirnya membuat terdakwa marah dan keluar dari pengadilan dengan meludah ke tanah. Keberanian dan integritas Adi Andojo semakin terlihat ketika beliau akhirnya diangkat sebagai hakim agung pada tahun 1980.
Kemanusiaan, Demokrasi, dan Anti-Korupsi
Perjuangan Adi Andojo Soetjipto dalam menggaungkan semangat anti-korupsi dan melawan korupsi bahkan di internal lembaga sendiri membuka mata dan hati penulis bahwa masih ada harapan untuk negeri ini menjadi negeri yang bersih bebas dari cengkraman korupsi. Dalam gelapnya korupsi di republik ini, Adi Andojo Soetjipto muncul sebagai sosok pembawa pelita harapan. Beliau mengajarkan kita bahwa integritas dan keberanian adalah modal utama dalam memerangi korupsi yang telah menggurita di republik ini. Tidak peduli siapa yang dilawan, bagi beliau institusi pengadilan yang bersih adalah awal dari negara yang bersih. Pendapat beliau di dalam putusan perkara Mochtar Pakpahan dan keterlibatan beliau untuk membongkar kasus korupsi dalam perkara Gandhi Memorial School adalah bentuk perjuangan beliau dalam membela demokrasi dan memerangi korupsi di republik ini. Beliau memperlihatkan kepada kita bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar diucapkan dan dijargonkan namun dihidupkan melalui implementasi nyata dalam tugas dan kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang hakim agung, beliau menjadikan dirinya lebih agung daripada jabatannya. Beliau mampu menjadi teladan yang menginspirasi para hakim muda untuk tetap setia dengan nilai hidup integritas dan keberanian karena dengan integritas dan keberanian seorang hakim nantinya bisa menjadi hakim yang berkualitas.
Sebagai penutup dalam esai ini, penulis ingin menulis sebuah kutipan:
“Barangsiapa yang berjuang untuk demokrasi dan anti korupsi, maka ia sedang berjuang bagi kemanusiaan”